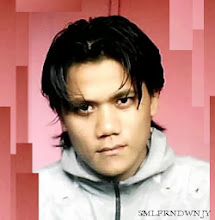Tidak seperti halnya belajar menurut perspektif behavioris dimana perilaku manusia tunduk pada peneguhan dan hukuman, pada perspektif kognitif ternyata ditemui tiap individu justru merencakan respons perilakunya, menggunakan berbagai cara yang bisa membantu dia mengingat serta mengelola pengetahuan secara unik dan lebih berarti. Teori belajar yang berasal dari aliran psikologi kognitif ini menelaah bagaimana orang berpikir, mempelajari konsep dan menyelesaikan masalah. Hal yang menjadi pembahasan sehubungan dengan teori belajar ini adalah tentang jenis pengetahuan dan memori.
Jenis Pengetahuan
Menurut pendekatan kognitif yang mutakhir, elemen terpenting dalam proses belajar adalah pengetahuan yang dimiliki oleh tiap individu kepada situasi belajar. Dengan kata lain apa yang telah kita diketahui akan sangat menentukan apa yang akan menjadi perhatian, dipersepsi, dipelajari, diingat ataupun dilupakan. Pengetahuan bukan hanya hasil dari proses belajar sebelumnya, tapi juga akan membimbing proses belajar berikutnya. Berbagai riset terapan tentang hal ini telah banyak dilakukan dan makin membuktikan bahwa pengetahuan dasar yang luas ternyata lebih penting dibanding strategi belajar yang terbaik yang tersedia sekalipun. Terlebih bila pengetahuan dan wawasan yang luas ini disertai dengan strategi yang baik tentu akan membawa hasil lebih baik lagi tentunya.
Perspektif kognitif membagi jenis pengetahuan menjadi tiga bagian, yaitu:
Pengetahuan Deklaratif, yaitu pengetahuan yang bisa dideklarasikan biasanya dalam bentuk kata atau singkatnya pengetahuan konseptual.
Pengetahuan Prosedural, yaitu pengetahuan tentang tahapan yang harus dilakukan misalnya dalam hal pembagian satu bilangan ataupun cara kita mengemudikan sepeda, singkatnya “pengetahuan bagaimana”.
Pengetahuan Kondisional, adalah pengetahuan dalam hal “kapan dan mengapa” pengetahuan deklaratif dan prosedural digunakan.
Pengetahuan deklaratif rentangnya sangat beragam, bisa berupa pengetahuan tentang fakta (misalnya, bumi berputar mengelingi matahari dalam kurun waktu tertentu), generalisasi (setiap benda yang di lempar ke angkasa akan jatuh ke bumi karena adanya gaya gravitasi), pengalaman pribadi (apa yang diajarkan oleh guru sains secara menyenangkan) atau aturan (untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan maka pembilang harus disamakan terlebih dahulu).
Menyatakan proses penjumlahan atau pengurangan pada bilangan pecahan menunjukkan pengetahuan deklaratif, namun bila siswa mampu mengerjakan perhitungan tersebut maka dia sudah memiliki pengetahuan prosedural. Guru dan siswa yang mampu menyelesaikan soal melalui rumus tertentu atau menterjemahkan teks bahasa Inggris adalah contoh kemampuan pengetahuan prosedural lainnya. Seperti halnya siswa yang mampu berenang dalam satu gaya tertentu, berarti dia sudah menguasai pengetahuan prosedural hal tersebut, dengan kata lain penguasaan pengetahuan ini juga dicirikan oleh praktek yang dilakukan.
Sedangkan pengetahuan kondisional adalah kemampuan untuk dapat mengaplikasikan kedua jenis pengetahuan di atas. Dalam menyelesaikan persoalan perhitungan kimia misalnya, siswa harus dapat mengidentifikasi terlebih dahulu persamaan apa yang perlu dipakai (pengetahuan deklaratif) sebelum melakukan proses perhitungan (pengetahuan prosedural). Pengetahuan kondisional ini jadinya merupakan hal yang penting dimiliki siswa, karena menentukan penggunaan konsep dan prosedur yang tepat. Terkadang siswa mengetahui fakta dan dapat melakukan satu prosedur pemecahan masalah tertentu, namun sayangnya mengaplikasikannya pada waktu dan tempat yang kurang tepat.
Hal yang sangat penting jadinya untuk mengidentifikasi jenis pengetahuan ini bagi guru ketika mengajar. Mempelajari informasi tentang pokok bahasan tertentu tidak selalu menyebabkan siswa akan menggunakan informasi tersebut. Tidak juga latihan menyelesaikan banyak soal pada topik bahasan tertentu, akan membantu mereka memahami satu prinsip lebih mendalam. Mengetahui sesuatu topik, mengetahui prosedural penyelesaian masalah serta tahu kapan dan mengapa menggunakan pengetahuan tersebut adalah hasil belajar yang berbeda-beda, dan tentu saja ini perlu diajarkan dengan cara yang berbeda pula.
Model Pengolahan Informasi
Untuk menggunakan tiga jenis pengetahuan di atas, tentunya kita harus dapat mengingatnya dengan baik. Hal berikutnya teori belajar yang dibahas dalam perspektif kognitif ini adalah tentang bagaimana individu mengingat dan bagian apa saja dari memori yang bekerja dalam proses berpikir seperti pada pemecahan masalah. Model pengolahan informasi merupakan salah satu model dari perspektif teori belajar ini yang menjelaskan kerja memori manusia sesuai dengan analogi komputer, yang meliputi tiga macam sistem penyimpanan ingatan: memori sensori, memori kerja dan memori jangka panjang.
· Memori Sensori adalah sistem mengingat stimuli secara cepat sehingga analisis persepsi dapat terjadi.
· Memori Kerja atau memori jangka pendek, menyimpan lima sampai sembilan informasi pada satu waktu sampai sekitar 20 detik, yang cukup lama untuk pengolahan informasi terjadi. Informasi yang dikodekan (decode) serta persepsi tiap individu akan menentukan apa yang perlu disimpan di memori kerja ini.
· Memori Jangka Panjang menyimpan informasi yang sangat besar dalam waktu yang lama. Informasi di dalamnya disimpan dalam bentuk secara verbal dan visual.
Memori Sensori
Memori sensori adalah sistem yang bekerja seketika melalui alat indera dinama kita memberikan arti kepada stimuli yang datang dinamakan persepsi. Arti yang diberikan berasal dari realitas objektif serta dari pengetahuan kita sebelumnya. Contohnya, suatu symbol ‘l’ akan dipersepsi sebagai huruf alpabet tertentu kalau kita menggolongkannya dalam urutan j, k. l, m; namun dalam kesempatan berbeda seperti l, 2, 3, 4 maka symbol yang sama bermakna angka satu. Memori sensori akan menangkap stimuli dan mempersepsi, atau memberikan makna; dalam hal ‘l’ konteks dan pengetahuan kita akan menentukan makna yang akan diberikan, bagi seseorang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang angka atau huruf, maka symbol itu kemungkinan tidak bermakna apapun. Misalnya teks yang Anda baca saat ini akan dipersepsi berbeda oleh orang lain yang tidak mengerti bahasa Indonesia ataupun yang buta huruf, walaupun matanya melihat deretan simbol yang sama seperti Anda; ataupun saat kita membaca huruf kanji dari koran berbahasa Jepang dimana kita tidak punya kemampuan untuk memahaminya. Memori sensori tidak hanya bekerja untuk simbol saja namun juga dalam hal warna, gerakan, suara, bau, suhu dan lainnya yang semuanya harus dipersepsi secara simultan. Namun karena keterbatasan kemampuan, kita hanya dapat memfokuskan pada beberapa stimuli saja dan mengingkari yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian sangatlah selektif; dengan kata lain saat perhatian penuh sangat diperlukan, biasanya stimuli lainnya akan ditolak.
Perhatian adalah tahap pertama dalam belajar. Siswa tidak dapat memahami apa yang mereka tidak kenali atau tidak dapat dipersepsi. Tentunya banyak faktor yang mempengaruhi perhatian siswa. Tampilan atau aksi yang dramatis dapat mencuri perhatian siswa pada awal pembelajaran. Cara lainnya adalah melalui perlakuan pada kata yang diucapkan atau ditulis oleh guru dengan warna yang kontras, digaris bawahi atau ditandai; memangil siswa secara acak, memberikan kejutan siswa, menanyakan hal yang menantang, memberikan masalah yang dilematis, mengubah metoda mengajar dan tugas, mengubah frekuensi suara dan jedanya akan dapat membantu menarik perhatian dari siswa. Namun menarik perhatian siswa adalah hal pertama, membuat mereka untuk tetap fokus pada pelajaran dan tugasnya juga hal yang kritis berikutnya harus dilakukan oleh guru.
Memori Kerja
Saat stimulus dipersepsi dan diubah menjadi suatu pola gambar atau suara, informasi yang didapat menjadi tersedia untuk proses selanjutnya. Memori kerja adalah tempat dimana informasi baru ini berada dan digabungkan dengan pengetahuan yang berasal dari memori jangka panjang. Kapasitas memori kerja ini sangat terbatas, dari berbagai eksperimen kapasitas yang dapat disimpan sekitar lima sampai sembilan hal baru dalam satu waktu. Satu nomor telepon sepanjang tujuh desimal dapat diingat oleh rata-rata manusia dewasa, namun hal yang berbeda bila disuruh untuk mengingat dua buah nomor telepon (14 desimal). Kita tidak dapat memanggil kedua nomor telepon tadi karena terbatasnya kapasitas memori kerja ini. Hal lainnya dari memori kerja ini adalah waktu yang digunakannya pun hanya sekitar 5 sampai 20 detik saja. Namun walaupun begitu waktu tersebut sangat cukup misalnya untuk mengingat dan memahami apa yang anda baca dalam bagian awal kalimat ini sebelum mencapai akhir kalimat. Tanpa adanya memori kerja, kita tidak bisa memahami susunan kata dalam satu kalimat dan gabungan antara kalimat yang berdekatan.
Karena sedikit dan sempitnya memori ini bekerja, maka jenis memori ini harus terus diaktifkan, kalau tidak maka informasi yang didapat menjadi hilang. Supaya apa yang diingat bisa lebih panjang dari 20 detik, kebanyakan orang memakai strategi tertentu untuk mengingatnya. Cara yang pertama adalah strategi latihan yang terbagi menjadi pengelolaan dan elaboratif. Latihan pengelolaan dilakukan dengan pengulangan informasi di pikiran anda. Sepanjang anda terus melakukan pengulangan informasi, hal itu akan berada di memori kerja. Cara ini dapat berguna untuk mengingat sesuatu, seperti nomor telepon, yang kemudian untuk dipergunakan dan setelah itu tidak perlu diingat lagi. Cara latihan elaboratif adalah dengan menghubungkan sesuatu yang baru dengan apa yang sudah diketahui, yaitu informasi yang sudah terdapat di memori jangka panjang. Latihan elaboratif ini tidak hanya meningkatkan memori kerja, tetapi membantu memindahkan informasi memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Cara kedua adalah dengan pengelompokkan (chunking) yang dipergunakan untuk menanggulangi terbatasnya kapasitas memori kerja. Banyaknya bit informasi, bukannya ukuran setiap bit, adalah sisi keterbatasan memori kerja. Kita dapat mengingat informasi lebih banyak jika dapat mengelompokkan tiap-tiap bit menjadi unit yang berarti. Deretan enam angka seperti 1, 5, 1, 8, 2, dan 0 akan lebih mudah diingat dalam bentuk dua digit (15, 18 dan 20) atau tiga digit (151, 820). Jika dilakukan cara ini, maka kita cukup perlu mengingat dua atau tiga informasi saja dalam satu waktu dibanding enam buah.